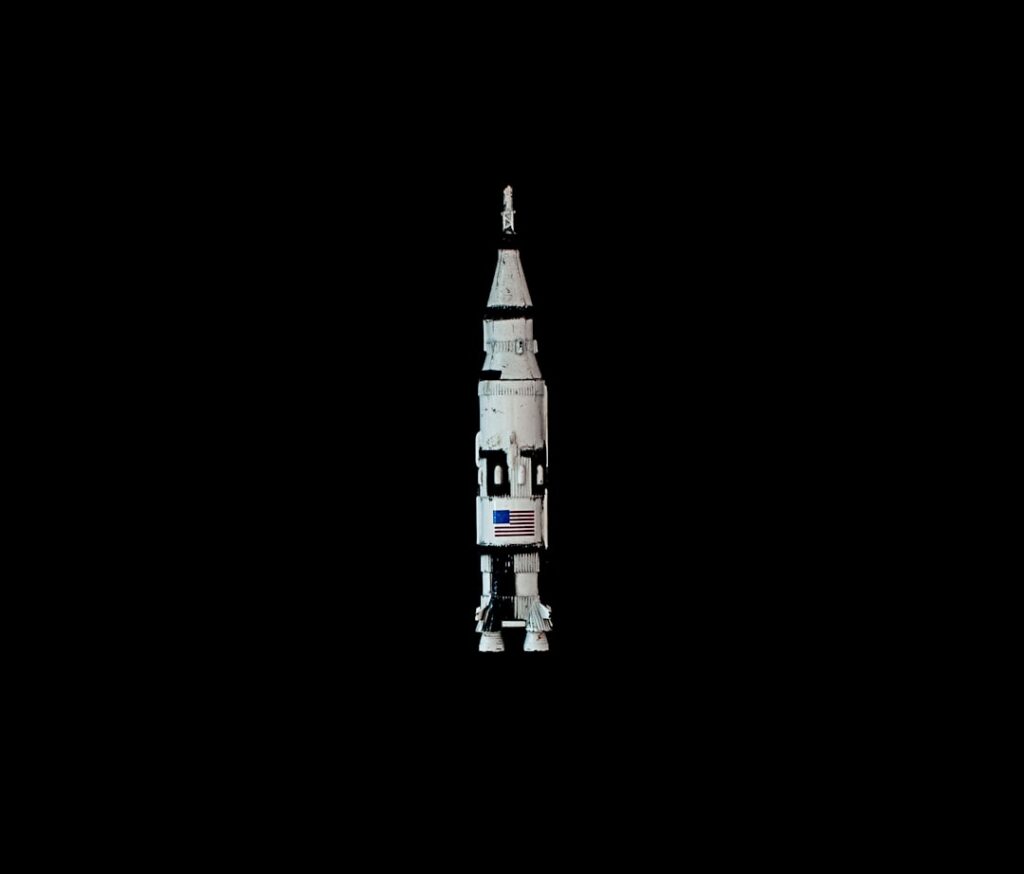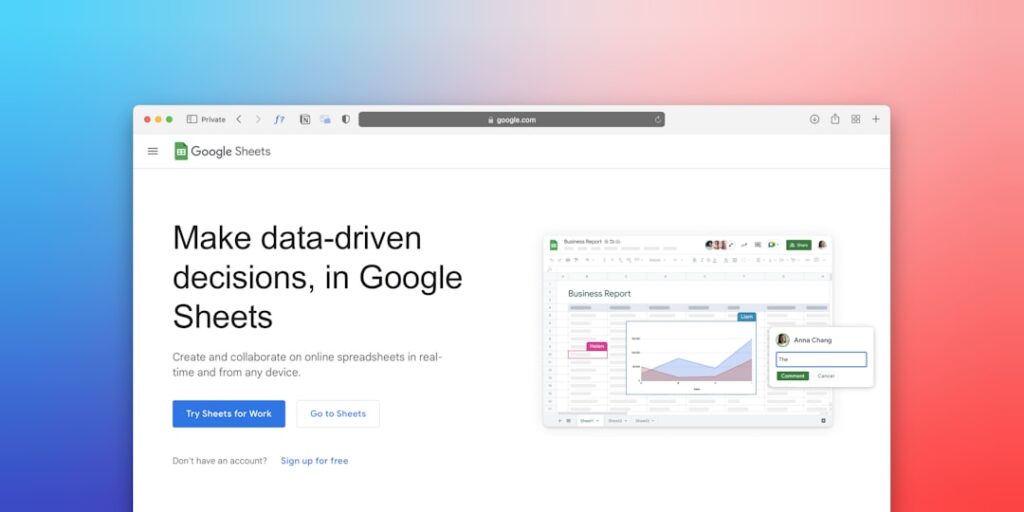Jakarta, CNN Indonesia — Negara-negara di berbagai belahan dunia berlomba menambah kapasitas energi terbarukan, bahkan di wilayah yang sebelumnya tak terduga. Para analis menilai, ini bisa menjadi awal era energi baru yang ditopang Matahari dan angin.
Pada paruh pertama 2025, energi terbarukan untuk pertama kalinya melampaui batu bara sebagai sumber listrik global terbesar. Tonggak ini dinilai krusial karena sektor energi merupakan penyumbang emisi terbesar di dunia.
Listrik bersih juga menjadi kunci untuk menekan emisi di sektor lain, termasuk transportasi dan industri berat. Kenaikan pesat ini diperkirakan akan terus tumbuh secara eksponensial seiring semakin murahnya teknologi tenaga surya, angin, dan baterai dibandingkan bahan bakar fosil.
Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan kapasitas energi terbarukan global akan berlipat ganda dalam lima tahun ke depan bertambah sekitar 4.600 gigawatt (GW), setara dengan total kapasitas listrik China, Uni Eropa, dan Jepang digabungkan.
“Tidak ada jalan kembali,” kata analis listrik senior Ember, Malgorzata Wiatros-Motyka, mengutip CNN, Jumat (7/11).
Meski begitu, para ahli mengingatkan bahwa lonjakan ini belum otomatis menurunkan emisi global. Permintaan energi yang tumbuh cepat membuat energi bersih di banyak negara belum sepenuhnya menggantikan bahan bakar fosil. Akibatnya, tingkat polusi masih meningkat dan risiko dampak iklim ekstrem tetap membayangi.
“Transformasi penuh sektor listrik ke energi bersih bukan sesuatu yang pasti. Kita belum bisa memastikan keberhasilannya,” ujar Hannah Pitt dari Rhodium Group.
Masih ‘Tersandera’ Fosil
Negara-negara pengemisi terbesar dunia mulai beralih ke energi bersih, terutama karena alasan ekonomi. Energi terbarukan khususnya surya kini menjadi pilihan paling murah.
China menjadi contoh paling mencolok. Dalam setahun terakhir, negara ini memasang pembangkit angin dan surya lebih banyak daripada total kapasitas yang saat ini beroperasi di Amerika Serikat.
Hingga akhir tahun lalu, kapasitas tenaga surya dan angin di China telah menembus 1.400 GW, dengan tambahan 500 GW lainnya masih dalam tahap konstruksi. Amerika Serikat, meski dukungan politik terhadap energi bersih melemah di era Presiden Donald Trump, tetap mencatat pertumbuhan signifikan. Tenaga Angin dan surya mendominasi kapasitas listrik baru, dan AS kini berada di peringkat kedua dunia dalam pertumbuhan tenaga surya, di bawah China.
Dorongan ini datang dari perusahaan yang mengejar kredit pajak era Biden sebelum berakhir, serta fakta bahwa surya, baterai, dan angin darat tetap menjadi energi termurah dan tercepat untuk dibangun.
Uni Eropa, dengan dukungan kebijakan energi hijau, menargetkan hampir 43 persen bauran energinya berasal dari energi terbarukan pada akhir dekade ini.
Namun, transisi ini masih setengah hati. China mencatat produksi batu bara tertinggi dalam satu dekade terakhir. Amerika Serikat di sisi lain juga kembali meningkatkan ketergantungan pada PLTU, sementara India memperluas penggunaan fosil demi pertumbuhan ekonomi, dan Uni Eropa terpaksa meningkatkan pembangkit fosil akibat kekeringan yang menurunkan produksi angin dan air.
Negara-negara Tak Terduga
Menariknya, percepatan transisi energi justru terjadi di banyak negara berkembang. Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, hingga Timur Tengah mulai melompat ke energi terbarukan, didorong oleh masuknya teknologi murah dari China.
“Kami melihat negara-negara emerging memanfaatkan skala global untuk langsung melompat ke era energi berikutnya,” kata Lars Nitter Havro dari Rystad Energy.
Nepal, misalnya, kini mencatat hampir 76 persen penjualan kendaraan barunya adalah kendaraan listrik, ditopang impor mobil listrik dari China dan pasokan listrik hidro yang melimpah. Pakistan, Chile, Yunani, dan Hungaria juga mencatat lonjakan cepat. Pakistan bahkan menaikkan pangsa surya dari nol menjadi 30 persen hanya dalam enam tahun.
Hungaria mengalami ledakan energi surya meski dipimpin pemerintahan sayap kanan, Chile memanfaatkan Gurun Atacama, dan Yunani mengoptimalkan bukit serta pulau Mediterania.
Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa energi terbarukan membutuhkan dukungan sistem penyimpanan seperti baterai. Tanpa itu, ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas masih akan berlanjut di banyak negara hingga 2050.
Bagaimana di Indonesia?
Di tengah derap global ini, Indonesia berada di persimpangan. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya terhadap transisi energi.
Di KTT BRICS dan pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, ia bahkan menyebut target 100 persen energi terbarukan bisa tercapai pada 2034-2035 jauh lebih cepat dari target awal 2040.
Namun ambisi ini belum tertuang dalam dokumen resmi energi nasional. Peta jalan yang masih menjadi acuan adalah RUPTL 2025-2034, yang menargetkan 76 persen kapasitas listrik berasal dari energi terbarukan pada 2034.
Dengan laju pertumbuhan energi baru dan terbarukan (EBT) saat ini yang hanya 1-2 persen per tahun, banyak pihak menilai target tersebut pun sulit dicapai tanpa perubahan radikal. Faktanya, target EBT Indonesia selama satu dekade terakhir tak pernah tercapai. Target 2023 bahkan direvisi turun dari 21 persen menjadi 17 persen.
Hambatan utamanya adalah pendanaan, dengan gap rata-rata US$7 miliar per tahun (setara dengan Rp113 triliun per tahun), ditambah regulasi berbelit dan komitmen politik yang inkonsisten.
Sementara itu, kapasitas PLTU batubara justru melonjak 6,5 kali lipat sejak 2000, didorong ekspansi PLTU captive untuk industri mineral. Lebih dari 12 GW PLTU baru beroperasi dalam lima tahun terakhir, meski sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami surplus.
Para pengamat menilai, jika Indonesia serius mengejar ketertinggalan, PLTS atap bisa menjadi jalan pintas. Potensi nasional diperkirakan mencapai 32,5 GW, tetapi realisasi hingga 2022 baru sekitar 80 MWp.
Pemerintah mengeklaim saat ini terus memacu percepatan transisi energi untuk memastikan puncak emisi nasional tidak bergeser melewati 2030.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan, pemerintah harus bekerja keras dalam lima tahun ke depan agar puncak emisi tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
“Kita akan berusaha mewujudkan net zero emission itu sampai dengan 2060 dan kalau kita lihat, kita 5 tahun ini harus sangat berusaha agar titik puncak emisinya tidak bergerak lebih dari 2030,” ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).
Ia mengingatkan, apabila puncak emisi bergeser lebih dari 2030, maka beban upaya penurunan emisi akan menjadi jauh lebih berat. Hal tersebut berpotensi memperpanjang dan memperdalam langkah mitigasi yang harus dilakukan pemerintah.